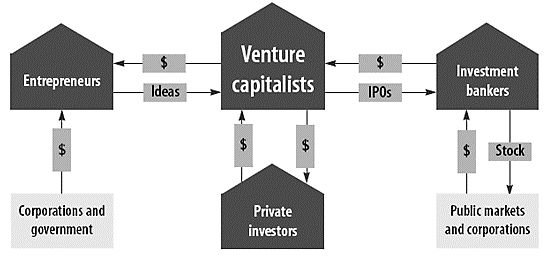Kebijakan Sosial: Kegagalan Kebijakan Sosial di Seluruh Dunia!
Istilah ‘kebijakan sosial’ yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan sosial. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan migrasi desa-kota, distribusi pendapatan secara keseluruhan akan menjadi lebih timpang pada tahap awal pembangunan dan selanjutnya akan semakin merata. Masalah sosial kemudian dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari masalah politik dan ekonomi negara. Sejarah sosial tidak akan lepas dari sejarah politik dan ekonomi pada periode manapun. Selama berabad-abad itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah agama sejak amal itu sendiri dilembagakan.
Pembentukan disiplin kebijakan sosial muncul dari politik kolektivisme dan praktik intervensi negara untuk menangani masalah sosial di awal abad kedua puluh. Meskipun, telah ada intervensi negara yang signifikan pada abad ke-19 melalui misalnya hukum yang buruk, Undang-Undang Pabrik, standar kesehatan masyarakat, ketentuan pendidikan, penerimaan besar-besaran terhadap argumen prinsip kolektivisme tidak muncul sampai pergantian tahun. abad (Williams, 1989).
Menurut beberapa ilmuwan sosial seperti Ursekar, konsep kesejahteraan sosial muncul dari realisasi saling ketergantungan orang, bahwa orang-orang suatu negara adalah satu kesatuan organik yang terintegrasi dan tidak adil untuk menolak kesempatan untuk mencapai standar hidup untuk yang cacat (yaitu, bagian yang lebih lemah) dan bahwa hal itu akan menjadi penyangkalan terhadap keadilan sosio-ekonomi baginya dan bahwa tidak ada komunitas yang dapat maju kecuali semua bagiannya berkembang secara seragam (Ursekar, 1973).
Konsep kebijakan sosial terkait dengan keadilan sosial dan pembangunan sosial. Ini adalah metode di mana keadilan sosial dicapai dan pembangunan sosial dilakukan. Menurut Briggs, “Konsep ‘kebijakan sosial’ yang penting bagi sejarah modern berkaitan dengan perubahan persetujuan terhadap efisiensi dan ruang lingkup pemerintahan dan administrasi” (Briggs, 1972). Menurut definisi Briggs ini, oleh karena itu, bukan hanya perumusan kebijakan sosial tetapi implementasinya yang efektif adalah yang terpenting. Kedua, kebijakan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan aspirasi dan kemanfaatan masyarakat.
Dalam masyarakat Barat, sosialisme Fabian dianggap lebih condong ke arah keadilan sosial dan pembangunan sosial karena nilai-nilai dominan Fabianisme adalah kesetaraan, kebebasan, dan persekutuan. Fabian sangat berkomitmen pada kesetaraan demi keharmonisan sosial, efisiensi sosial, keadilan alam, dan realisasi potensi kolektif. Bersamaan dengan ini, mereka adalah orang-orang yang berperikemanusiaan, dan mereka mengutamakan pengentasan kesengsaraan dan mengutamakan kerja sama dan demokrasi.
Argumen mereka melawan kapitalisme adalah argumen moral. Itu adalah tindakan yang tidak etis, tidak adil, tidak demokratis. Inti dari transformasi ini adalah negara kesejahteraan yang dengan komitmennya untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan, keharmonisan sosial dan redistribusi kekayaan, dapat mempromosikan perubahan material dan memenangkan altruisme dan egalitarianisme rakyat (Williams, 1989).
Oleh karena itu, menurut William, kebijakan sosial yang berkaitan dengan pembangunan sosial memperoleh posisinya yang menonjol pada pergantian abad ke-20. Pemikiran Marxian yang berkembang, baik di kalangan kelas intelektual dan politik, maupun kelas apolitis lainnya, lebih menekankan pada kesejahteraan massa rakyat negara secara keseluruhan.
Baik negara-negara liberalis maupun sosialis memberikan arti penting yang optimal terhadap istilah ‘kebijakan sosial’ yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan sosial. Masalah sosial kemudian dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari masalah politik dan ekonomi negara. Sejarah sosial tidak akan lepas dari sejarah politik dan ekonomi pada periode manapun. Selama berabad-abad itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah agama sejak amal itu sendiri dilembagakan.
Seperti yang telah disebutkan, negara adalah institusi utama untuk melaksanakan kebijakan sosial untuk mencapai tujuan sosial. “Karena: (i) Negara memperluas kendalinya atas alat-alat produksi, secara bertahap atau dengan evolusioner yang tiba-tiba dan dengan demikian menjadi ciri utama pembangunan ekonomi; (ii) Kekuatan politik negara dipandang sebagai instrumen yang paling berguna untuk mengimplementasikan perubahan sosial dan mengadaptasi institusi sosial tradisional ke keadaan baru; (iii) Pembangunan sosial terutama merupakan hasil dari tindakan sadar oleh negara dalam kerangka rencana negara yang terkoordinasi dan serba ilusif” (Fusic, 1972).
Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh berbagai sarjana negara harus mengarahkan rencana aksinya untuk mencapai keadilan sosial dan menjadikannya negara kesejahteraan, karena dalam tatanan sosial yang timpang dan tidak adil, gangguan dan disintegritas sangat mungkin terjadi.
Menggambar pada kekayaan penelitian empiris di bidang hubungan percobaan industri, Gold-Thorpe berusaha untuk menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial yang ditandai dalam masyarakat modern harus berfungsi untuk melemahkan integrasi sosial, dan tanpa mengurangi ketidaksetaraan secara tajam, pola anomik tidak dapat dikurangi dalam masyarakat tersebut. . Ia berusaha menunjukkan bahwa hubungan industrial yang ‘tidak tertib’ dan ‘permainan upah’ adalah konsekuensi dari pola ketimpangan yang tidak dapat dilegitimasi. Sifat ‘tidak berprinsip’ dari distribusi imbalan yang tidak merata berfungsi sebagai pengaruh destabilisasi yang terus-menerus dan menyebabkan ketidakpuasan di antara setiap kelompok pekerja.
Goldthorpe percaya bahwa dalam analisis masalah terapan tertentu, sebagai tugas sosiolog terapan, tidak mengambil pola ketidaksetaraan yang ada seperti yang diberikan, karena tidak ada solusi untuk masalah sosial yang ada dalam sistem ketidaksetaraan. Sebaliknya, sosiolog terapan harus menghadapi kebutuhan yang seringkali tidak menyenangkan untuk menjelaskan bahwa konflik dan kurangnya integrasi secara rutin dihasilkan dari konsekuensi distribusi sumber daya yang sangat tidak merata (Goldthorpe, 1974).
Oleh karena itu, kesejahteraan sosial harus menjadi isu utama kebijakan sosial. Beberapa sarjana percaya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan menjaga kesejahteraan sosial dan membawa pemerataan dan keadilan sosial. Namun, beberapa bukti empiris yang dilaporkan sejauh ini tidak mendukung argumen ini.
Salah satu studi pertama yang cukup komprehensif tentang distribusi dan pertumbuhan pendapatan adalah penelitian Kuznets. Untuk membandingkan distribusi pendapatan lintas negara, Kuznets mampu menghasilkan data yang dapat digunakan di enam belas negara, sembilan di antaranya sedang berkembang.
Pengamatannya adalah:
(i) Bagian pendapatan dari kelompok berpenghasilan tertinggi di negara berkembang jauh lebih besar daripada bagian kelompok yang sama di negara maju;
(ii) Pangsa pendapatan kuintil terbawah hampir sama di negara maju dan negara berkembang;
(iii) Ada kesetaraan yang lebih besar di antara kelompok berpenghasilan menengah di LDC daripada di kelompok semacam itu di DC, seperti yang dikatakannya, “jika ada ketimpangan yang lebih besar di LDC di bagian atas struktur pendapatan, dan tingkat ketimpangan yang sama di bagian bawah, harus ada persamaan yang lebih besar di kelompok tengah” (Kuznets, 1963).
Sesuai temuan Adelman dan Morris, pada tingkat pembangunan terendah, pertumbuhan cenderung meningkatkan ketimpangan. Secara umum, di negara-negara termiskin, pertumbuhan merugikan segmen penduduk yang lebih miskin (Adelman dan Morris, 1973). Menurut Robinson, karena adanya faktor-faktor lain, yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat dan migrasi desa-kota, distribusi pendapatan secara keseluruhan akan menjadi lebih tidak merata selama tahap awal pembangunan dan kemudian menjadi lebih merata (Robinson, 1976).
Namun, studi Oshima tentang ketimpangan di negara-negara Asia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mengurangi ketimpangan, sehingga membantah pandangan Robinson. Kesimpulan utamanya adalah bahwa penekanan kebijakan yang tidak semestinya pada industrialisasi dapat menyebabkan pengangguran, urbanisasi yang berlebihan, ketidakseimbangan regional, dan melebarnya ketimpangan (Oshima, 1970).
Weisskoff meneliti pergeseran dari pertanian ke kegiatan ekonomi non-pertanian dan menemukan peningkatan ketimpangan secara keseluruhan (Weisskoff 1970). Demikian pula dalam studi ketimpangan di India, Swamy menyimpulkan bahwa ketimpangan meningkat lebih besar di sektor industri (85%) dibandingkan di sektor pertanian (15%). Dengan kata lain, ketimpangan antarsektoral lebih banyak daripada ketimpangan intrasektoral (Swamy, 1967). Studi Berry (1974) tentang Kolombia menunjukkan ketidaksetaraan yang terus meningkat antara sektor pertanian dan perekonomian Kolombia lainnya sejak tahun 1930-an, meskipun terjadi pertumbuhan produk per kapita secara keseluruhan.
Karena ketimpangan yang ekstrim, manfaat mutlak dari kebijakan publik tertentu yang diterima oleh kelompok berpendapatan tinggi jauh melebihi keuntungan yang diperoleh kaum miskin (De Wulf, 1974). Studi lapangan tentang pendidikan tinggi Kenya menunjukkan bahwa ada “proses sistematis yang melawan orang miskin,” yang cenderung melanggengkan ketidaksetaraan yang ada di sana (Fields, 1975).
Program ketenagakerjaan telah menarik perhatian banyak ilmuwan sosial, dan proposal untuk mengatasi masalah pengangguran dan distribusi pendapatan yang tidak merata menghiasi hampir semua rencana pembangunan. Namun, kebijakan negara sekali lagi bertentangan dengan lapangan kerja dan pemerataan. Misalnya, teknologi pengganti tenaga kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghambat lapangan kerja tetapi juga distribusi pemerataan pendapatan.
Webb, sesuai pengamatannya di Peru menunjukkan bahwa pendapatan non-buruh bertanggung jawab atas ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan tenaga kerja (Webb, 1972). Oleh karena itu, Jarvis menganjurkan tidak hanya untuk kebijakan ketenagakerjaan yang benar tetapi peran pemerintah yang lebih langsung dalam distribusi pendapatan (Jarvis, 1974).
Juga telah dilaporkan oleh para sarjana bahwa kebijakan ekonomi pemerintah, yaitu kebijakan stabilisasi menyebabkan peningkatan ketimpangan. Hal ini telah dilaporkan dari Indonesia (Arndt, 1975) dan Brazil (Wells, 1974). Berbagai penelitian lain yang berkaitan dengan pertumbuhan dan ketimpangan telah diulas oleh Loehr (Loehr, 1977). Loehr telah merangkum beberapa faktor yang bertanggung jawab atas ketimpangan dan kemiskinan yang parah.
Ini adalah: (i) Distribusi sumber daya manusia yang tidak merata menyebabkan perbedaan yang lebar dalam produktivitas dan pendapatan, (ii) Hambatan mobilitas ekonomi lebih besar di negara berkembang daripada di negara maju. Hambatan ini dapat berupa rasisme terbuka, undang-undang yang membatasi , kualifikasi pekerjaan yang tidak realistis, ketidaktahuan, atau tradisi, (iii) Struktur ekonomi suatu negara mungkin cenderung memusatkan pendapatan di beberapa tangan. Struktur ini dapat menentukan kepemilikan properti dan lokasi sumber daya tertentu seperti mineral, (iv) Organisasi sosial dan politik suatu negara mungkin tidak kondusif bagi pembagian pendapatan secara luas, (v) Dualisme, pada elemen struktur ekonomi dapat menciptakan situasi di mana terdapat kecenderungan ‘otomatis’ agar pendapatan menjadi terkonsentrasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Kemiskinan adalah bidang lain di mana kebijakan sosial diperhatikan. Meskipun pendapatan nasional meningkat, kebijakan sosial yang cacat tidak dapat membebaskan dunia dari kemiskinan dan kelaparan. Hasil dari pendapatan nasional belum mencapai tingkat yang signifikan bagi kaum miskin di sebagian besar negara berkembang, meskipun ada pertumbuhan; misalnya menurut McNamara terlepas dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang tahun 1960-an, orang miskin tidak mendapatkan keuntungan dari ini (McNamara, 1973). Dia juga membedakan tiga kategori besar kemiskinan di negara berkembang sebagai berikut.
Pertama, terdapat kemiskinan yang parah pada umumnya di negara-negara kecil yang hanya memiliki sedikit sumber daya – alam, keuangan atau keterampilan – yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan. Ada begitu sedikit kekayaan di negara-negara ini sehingga bahkan jika didistribusikan secara lebih merata, hampir setiap orang masih sangat miskin. Ada dua puluh lima negara seperti itu, dengan populasi berjumlah 140 juta. UNO telah menetapkan ini sebagai LDC dan tindakan bantuan khusus untuk mereka telah disetujui.
Kedua, ada kemiskinan yang ditemukan di daerah miskin tertentu di sebagian besar negara berkembang yang lebih besar – misalnya, republik selatan Yugoslavia, Brasil timur laut, dan Thailand timur laut. Integrasi wilayah-wilayah ini ke dalam bagian-bagian ekonomi yang tumbuh lebih cepat seringkali menimbulkan masalah budaya dan ekonomi yang sulit. Akan tetapi, wilayah-wilayah ini mudah diidentifikasi secara geografis, dan dimungkinkan untuk menyusun dan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kapasitas produktif dan pendapatan penduduk mereka, berdasarkan ciri-ciri geografis wilayah tersebut.
Kategori kemiskinan ketiga adalah yang paling luas, paling meresap, dan paling gigih dari semuanya. Ini adalah kemiskinan strata berpenghasilan rendah kira-kira 40 persen termiskin dari total populasi di semua negara berkembang. Merekalah yang, terlepas dari pertumbuhan ekonomi negara mereka, tetap terjebak dalam kondisi kekurangan yang berada di bawah kekurangan rasional dari kesusilaan manusia.
McNamara mengkritik kebijakan sosial dari berbagai negara bagian yang tidak mampu mengatasi kemiskinan dengan kata-kata berikut: “Ini bukan sekadar kemiskinan negara yang sangat tertinggal atau wilayah geografis yang sangat terbelakang di negara yang maju pesat. Sebaliknya, kemiskinan orang-orang ini tersebar luas di setiap negara berkembang yang, untuk alasan apa pun, berada di luar jangkauan kekuatan pasar dan layanan publik yang ada. Kemiskinan massa penduduk itulah yang tidak dicakup oleh kebijakan pemerintah saat ini secara memadai dan bantuan eksternal tidak dapat secara langsung menjangkau” (McNamara, 1973).
Idris Cox, dalam karya monumentalnya The Hungry Half, telah menjelaskan secara lebih rinci berbagai penyakit sosial yang dihadapi oleh masyarakat miskin di dunia berkembang dan terbelakang. Dia, melalui contoh-contoh dari berbagai survei, pengamatan, studi, dll., Keterampilan menyoroti sepenuhnya masalah kelaparan, kehausan, melek huruf dan pendidikan, tempat tinggal, pakaian, penyakit, kesehatan, kelaparan dll., dari massa miskin ini. Menurutnya Asia dan Afrika adalah yang terburuk tetapi di Amerika Latin kondisinya hampir tidak lebih baik (Cox, 1970).
Tentang kondisi umum dari massa yang miskin dan tereksploitasi ini, dia mencatat: “Kondisi di mana mayoritas rakyat di negara-negara berkembang hidup jauh lebih buruk daripada hari-hari mengerikan di Inggris pada masa-masa awal Revolusi Industri dua abad yang lalu. Beberapa dari mereka memiliki rumah yang layak. Di desa mereka tinggal di gubuk-gubuk lumpur, sebagian besar tanpa pipa air, drainase, gas atau listrik. Mereka hanya menambah eksistensi telanjang. Di kota-kota, mereka tinggal di gubuk timah, dengan selokan terbuka yang mengalir melalui apa yang berpura-pura menjadi jalan tetapi tidak lebih dari jalur gerobak yang kasar. Mereka jarang memiliki pasokan air perpipaan atau sanitasi apa pun dan sangat padat” (Cox, 1970).
Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa kebijakan negara agak bertentangan dengan pemerataan dan keadilan yang menyebabkan sejumlah besar orang miskin atau kelaparan di negara berkembang. Myrdal, menyebut kebijakan ini sebagai ‘kebijakan lunak’. Negara tidak mengambil sikap radikal untuk mencapai pemerataan dan keadilan sosial karena ia mengkhawatirkan kelas-kelas kepentingan lainnya. Akibatnya memunculkan kebijakan lunak yang justru mengakumulasi kemiskinan dan krisis lainnya (Myrdal, 1971). Selain soft stand atau kebijakan, kelemahan lain dalam kebijakan dan korupsi yang berlebihan, menurut dia, merupakan ‘tantangan kemiskinan dunia’.
Dia juga mengkritik kebijakan pertanian, kebijakan kependudukan, kebijakan pendidikan, dll., dari negara berkembang yang tidak memadai dan miskin, dan karena itu menambah bahan bakar ke dalam api. Myrdal melihat ketimpangan sistem adalah faktor yang paling kejam. Dalam kata-katanya sendiri: “…bahwa ketimpangan dan kecenderungan meningkatnya ketimpangan berdiri sebagai kompleks hambatan dan hambatan terhadap pembangunan dan bahwa, akibatnya, ada kebutuhan mendesak untuk membalikkan kecenderungan dan menciptakan kesetaraan yang lebih besar sebagai syarat untuk mempercepat pembangunan ”.
Selain itu, kebijakan pertumbuhan yang diadopsi oleh negara berkembang justru bertentangan dengan keadilan sosial sehingga memperlebar ketimpangan sosial. Hal ini dicontohkan dengan kutipan berikut: “Ada konflik … antara tujuan pertumbuhan dan pemerataan … Ketimpangan pendapatan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan perbaikan nyata bagi kelompok berpenghasilan rendah” (Papanek, 1967) . Oleh karena itu, sarjana seperti Paul Streeten menyerukan Pendekatan Manusia Dasar sebagai kebijakan yang tepat menggantikan Pendekatan Pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai keadilan sosial” (Streeten et al 1982).
Kegagalan Kebijakan Sosial:
Meskipun pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi ketimpangan, pembangunan sosial belum terjadi, yaitu pemerataan dan keadilan, karena beberapa alasan, beberapa di antaranya telah dibahas di atas.
Beberapa cendekiawan seperti Rossi berpandangan bahwa populasi sasaran akan sulit untuk didefinisikan atau dipengaruhi, program yang diusulkan akan sulit diakses, dan program alternatif tidak dapat dengan mudah dipesan dalam hal keunggulan atau inferioritasnya. Dia berpendapat bahwa pendekatan analisis biaya-manfaat dalam pengambilan keputusan akan lebih rasional secara eksplisit.
Pendekatan ini, baginya, dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana memilih di antara pendekatan-pendekatan alternatif dalam mencapai serangkaian tujuan sosial tertentu (Rossi, 1972). Namun, bukan cost-benefit, tetapi melakukan upaya dan pengorbanan yang sungguh-sungguh dengan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan, tampaknya lebih baik. Karena kualitas hidup, pemerataan dan keadilan tidak dapat diuji melalui analisis biaya-manfaat.
Sejumlah teori dikembangkan untuk menjelaskan kegagalan dalam proses kebijakan sosial; mereka berbeda dalam pandangan mereka tentang penyebab utama kerusakan tersebut.
Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga aliran pemikiran:
(i) Kegagalan dalam rancangan kebijakan;
(ii) Kegagalan dalam pengelolaan hubungan antar dan intra organisasi; dan
(iii) Tumbuhnya penodaan administratif di kalangan pekerja garis depan (Gummer, 1990).
Menurut Gummer, perspektif ini kira-kira sesuai dengan apa yang disebut Rein dan Robin Ovitz sebagai tiga ‘keharusan’, yang harus diperhatikan oleh para aktor dalam proses kebijakan: Keharusan hukum untuk melakukan apa yang diharuskan secara hukum; keharusan birokrasi rasional untuk melakukan apa yang dapat membangun kesepakatan di antara pihak-pihak berpengaruh yang bersaing yang memiliki andil dalam hasilnya.
Setiap keharusan berusaha untuk mencapai tujuan yang berbeda, sehingga menciptakan sistem permintaan yang berpotensi bertentangan pada pembuat kebijakan, administrator program, dan penyedia layanan. Ketika tujuan dan kepentingan aktor tersebut dan aktor lainnya (pengguna layanan dan perwakilan masyarakat umum) berkonflik, proses implementasi menjadi terpolitisasi, karena berbagai pihak berusaha memajukan kepentingan masing-masing (ibid.). Dengan kata lain, menurut Gummer persaingan internal di antara kelas elit yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial merupakan penyebab kegagalan kebijakan sosial dalam mencapai tujuan keadilan sosial, pemerataan dan pembangunan.
Berbagai faktor lain juga berakar pada kegagalan kebijakan seperti itu, “ras, gender, kasta, kelas, daerah dll., faktor memainkan peran penting dalam diskriminasi kategori tertentu (bagian, kelompok) yang atas namanya kebijakan dan program sosial dirumuskan tetapi benar-benar mereka yang tidak digunakan (diimplementasikan) secara praktis untuk peningkatan dan pembangunan mereka yang diarahkan atau ditargetkan oleh kebijakan. Oleh karena itu, peran ‘nilai’ sangat menentukan dalam menentukan keadilan sosial dan pembangunan sosial” (Hantal, 1996). Jadi, jika satu metode digunakan untuk memberantas masalah sosial, sebelum benar-benar memberantasnya, masalah lain akan terjadi, yang oleh Schaffer disebut ‘Ironi kesetaraan ‘ (Schaffer dan Lamb, 1981).
Sesuai pengamatan Schaffer, tindakan publik mungkin dimaksudkan untuk mengubah ‘ketidaksetaraan’ yang muncul dari pengoperasian institusi dan aturan (yaitu, pasar, agensi, hukum, struktur rumah tangga). Akan tetapi, ia melakukannya secara khas dan tidak dapat dihindari, dengan mendirikan lembaga-lembaga baru dan hasil dari pengucilan dan ketidaksetaraan, dan proses tersebut dapat berlanjut tanpa batas.
Di Inggris, misalnya, langkah-langkah untuk mengoreksi hasil pasar tenaga kerja – melalui kebijakan regional dan sistem pembayaran kesejahteraan – mengarah pada serangkaian kondisi yang kompleks tentang kelayakan pekerjaan , pengangguran, dan tunjangan tambahan dan pada waktunya untuk menetapkan aturan lebih lanjut. tentang banding dan pengecualian.
Sri Lanka, untuk mengambil contoh Dunia Ketiga, upaya untuk menangani kelas, etnis, basis regional yang seharusnya menyamakan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi tidak memiliki konsekuensi dari struktur banding yang baru. Sebaliknya, aturan eksklusi cenderung berkembang di sektor lain – yaitu, perubahan dalam kualifikasi pekerjaan dan kelayakan untuk kupon makanan, belum lagi perubahan konstitusional dan politik yang mempengaruhi minoritas Tamil, yang efeknya adalah menghasilkan jenis baru ‘ketidaksetaraan. ‘ hasil dalam program publik.
Contoh lain yang mencerahkan adalah kebijakan reservasi India yang diperluas ke Other Backward Classes (OBCs) sehingga membuat total reservasi pekerjaan pemerintah dan semi-pemerintah menjadi lima puluh persen. Oleh karena itu, ini memuaskan bagian yang lebih lemah, karena mereka sekarang akan memanfaatkan kesempatan ‘demokrasi perwakilan’.
Namun, dalam langkah yang tajam, pemerintah memulai privatisasi yang gencar dan pengurangan jabatan pemerintah dan semi-pemerintah, dengan demikian mengecualikan bagian yang lebih lemah yang mungkin berharap melalui reservasi mereka akan mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Oleh karena itu, kelangsungan reservasi yang lebih banyak hanya menjadi pencuci mata dan bentuk-bentuk penghalang baru yang didirikan untuk menghambat mobilitas sosial-ekonomi mereka,
Oleh karena itu, Schaffer dan Lamb mungkin benar ketika mengatakan bahwa kesetaraan sebagai konsep dan praktik di atas segalanya adalah fakta politik. “Itu” menurut mereka, “sebuah konstruksi ideologis tentang distribusi, tentang penunjukan sumber daya dalam masyarakat dan karenanya, bersifat politis dalam arti intervensi dalam perjuangan ide-ide politik. Dan itu bersifat politis dalam manifestasi prosedural/substantifnya, sebagai realisasi melalui tindakan negara dari aspek penting dari “interelasi ekonomi” politik (Schaffer dan Lamb, 1981).
Akhirnya, akan dinyatakan bahwa makna mulia apa pun yang mungkin terkandung dalam istilah ‘kesetaraan’, ‘keadilan’ dan ‘pembangunan’, ini tidak dapat dengan sendirinya cukup, kecuali dan sampai kebijakan sosial untuk memberikan bentuk yang bermakna pada konsep-konsep ini tidak dirumuskan secara jujur. dan praktis diimplementasikan dalam huruf dan semangat.